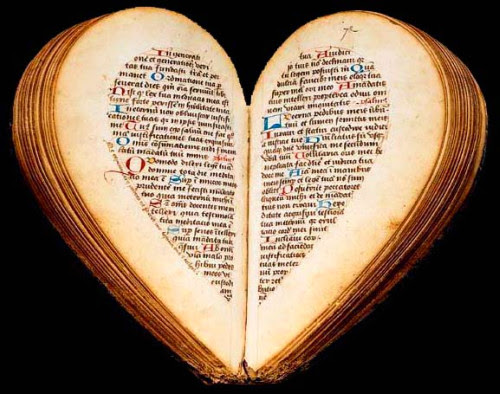Cerpen Jusuf AN, Dimuat Suara Merdeka Minggu, 11 Agustus 2013
BIARLAH Ayah saja yang menderita, dengan perut pias membusung, serta wajah ditumbuhi bercak-bercak yang setiap menit akan meledak buncahkan nanah dan darah. Biarlah Ayah tercekam dalam detik-detik sekarat di atas ranjangnya yang luas ditemani puluhan dokter paling handal di kota ini. Andai saja ia nanti mati, kami tak ingin menguburkannya. Kami tak ingin ia mengenalkan pada kami hal paling menakutkan bernama derita.
***
Setelah menyelesaikan kuliah, kami berempat disuruh memilih pekerjaan yang kami suka. Dan entah kenapa pilihan kami sama: membantu Ayah memimpin kota. Sebuah kota yang subur dengan kekayaan alam yang luar biasa melimpah. Sebuah kota yang penduduknya taat beribadah, tetapi gampang dibodohi.
Ayah memberi kami jabatan penting di kantor pusat kota. Ia juga mengajak kami mengikuti rapat-rapat politik bersama anak buahnya. Kami menyukai pekerjaan ini, pekerjaan yang tidak lebih dari sekadar bermain-main. Kami sering menyebutnya, permainan anak dewasa. Dalam permainan itu kami selalu menang. Siapa pun pasti akan puas setiap kali memenangkan permainan, termasuk juga kami.
Keluarga kami adalah yang terkaya di kota ini. Kami telah mendirikan puluhan pabrik, hotel, restoran, dan villa yang tersebar banyak tempat. Kekayaan yang kami miliki semakin melimpah, membuat banyak orang iri, terutama musuh-musuh politik yang tak pernah jera berusaha menjatuhkan Ayah, yang hanya segelintir orang saja sebenarnya. Meski begitu, dengan mudah mereka berhasil kami kalahkan. Tak ada yang bisa membongkar kebusukan di balik kekayaan yang kami miliki. Tak ada yang bisa membaca dan menandingi siasat politik kami.
***
Di hari ulang tahun Ayah ke-70 kami diundang di sebuah villa di pegunungan yang sejuk. Anehnya kami hanya boleh datang sendirian saja. Awalnya kami mengira Ayah sekedar ingin merayakan pesta dan bernostalgia serta memanjat doa panjang umur. Kami datang, membawa kado masing-masing. Ketiga kakakku, masing-masing memberi kado tombak, anak panah, dan tongkat yang mereka curi dari sebuah museum. Sementara aku membawa kue berbentuk hati yang ditaburi intan berlian.
Wajah Ayah nampak bahagia dan bangga punya anak seperti kami. "Terima kasih atas kedatangan kalian semua," katanya. Kami semua tersenyum. "Mungkin sudah waktunya untuk mengatakan hal penting bagi kalian. "
Kami berempat saling pandang. Sebuah pertanyaan tergambar dalam bola kecokelatan sepasang-pasang mata kami. Warisan?
Ayah seolah tahu isi pikiran kami, dengan cepat membantah, "Bukan masalah warisan yang ingin aku sampaikan, tapi sesuatu yang teramat penting." Serentak kami mengunci mulut rapat-rapat dan membuka telinga lebar-lebar. Andai pun benar soal warisan, kami mungkin akan mengatakan secara serentak, bahwa kami tak butuh lagi warisan, sebab kekayaan kami sungguh sudah sangat melimpah.
Sepasang bibir Ayah mulai bergetar lagi, "Kematian terasa semakin dekat." Sunyi berkuasa sejenak. Desau angin dan serangga malam yang merintih kedinginan melengkapi senyap. "Jika memang firasat Ayah ini benar, maka bersamaan dengan penguburan mayatku nanti, semua harta yang kita miliki akan ditelan bumi." Angin yang berdesir tiba-tiba diam. Suasana lengang mengkhidmati wajah kami yang tercengang. Mulanya kami mengira ucapan Ayah yang terdengar seperti syair itu hanya bercanda belaka. "Bercanda memang bisa membuat orang awet muda, tapi toh kita akan tetap mati juga." Lagi-lagi Ayah tahu isi otak kami.
“Mengapa bisa begitu?” tanyaku lantang.
Ayah menjelaskan, bahwa harta dan jabatan yang sekarang kami miliki sekarang sebenarnya bukan murni kerja kami. Melainkan bantuan para iblis. Jika Ayah meninggal nanti, iblis-iblis yang telah menjadi anak buah Ayah itu secara otomatis akan pergi dan membawa harta kekayaan kami ke alam mereka.
Bagi kami penjelasan Ayah tak masuk akal. Namun kemudian, Ayah mengatakannya lagi dengan suara lugas dan jelas. "Harta kalian akan tersedot ke bumi bersama penguburanku. Camkan itu!"
Bagaimanapun aku tak rela jika hartaku hilang. Bagaimana mungkin aku mengikhlaskan puluhan pabrik, hotel, restoran dan villaku yang tersebar di berbagai kota. Dan tiba-tiba saja seolah ada kekuatan yang menggerakkan tanganku untuk mencabut pistol, dan menodongkannya di kepala Ayah.
Ayah justru menyuruhku untuk menarik pelatuk pistol yang kugenggam dengan gemetaran. Keseriusan dalam kata-katanya nampak pada garis-garis keriput dan sorot matanya yang berwarna kecokelatan. Hampir saja peluru itu meletup dan menembus pelipisnya jika ketiga kakakku tidak cepat-cepat merebut pistol yang aku genggam dan menyeretku keluar setelah membisiku sesuatu.
Tanpa sepatah kata, kami berempat pergi dari villa itu. "Dengarkan dulu penjelasan Ayah! Meski kalian tidak menguburku, tapi…" Masih sempat kami mendengar Ayah berteriak memanggil kami untuk kembali. Tapi kami tak lagi peduli.
***
Akhirnya, kami menemukan strategi untuk menyelamatkan harta benda yang kami miliki. Jika Ayah meninggal nanti, kami tak akan kami mengubur mayatnya, sehingga harta kekayaan yang kami miliki akan selamat.
Sejak kecil kami dididik Ayah untuk percaya, bahwa tak satu pun orang di dunia ini yang sepenuhnya setia, dan mungkin sudah saatnya bagi kami untuk berkhianat, meski pada ayah kami sendiri.
Beberapa hari setelah perayaan ulang tahun itu, utusan yang kami tugaskan untuk membuntuti Ayah datang memberi kabar. Katanya, Ayah menderita sakit lambung. Dokter pribadinya mengatakan, ada gangguan pencernaan biasa dan akan sembuh satu jam setelah minum obat. Tapi penyakit itu justru kian mendera Ayah. Operasi bedah pun dilakukan. Tak ditemukan apa-apa dalam perut Ayah kecuali lima peluru yang entah kenapa bisa bersarang dalam perutnya. Mungkinkah Ayah telah menelan peluru itu bersama sebatang pisang seperti saat ia menguntal kapsul? Atau bisa jadi musuh-musuh politik Ayah yang telah meneluhnya.
Lima peluru yang berhasil diambil dalam operasi itu tidak serta-merta menyembuhkan rasa sakit dalam perut Ayah. Bahkan, perutnya kian lama kian membuncit. Bukan dalam hitungan bulan seperti perkembangan kandungan perempuan. Hanya dalam waktu seminggu perut Ayah telah menggelembung seperti balon, pias seperti warna cemas wajah kami.
Selang beberapa hari, kami kembali mendapat kabar, Ayah mengeluhkan gatal-gatal di wajahnya. Semua dokter paling handal di jagat ini kelimpungan dengan penyakit yang dideritanya. Belum pernah mereka mendapati penyakit aneh seperti itu. Jika Ayah orang miskin mungkin ia akan dibiarkan mati, kemudian mayatnya akan dijadikan bahan penelitian para dokter. Untungnya Ayah punya banyak simpanan uang untuk membayar dokter-dokter itu.
***
Setiap hari kami memantau keadaan Ayah dari layar kaca hasil rekaman kamera yang sengaja kami pasang di langit-langit kamar rawat Ayah. Dari layar kaca itu kami bisa melihat wajah Ayah dipenuhi bercak-bercak yang tiap menit meledak membuncahkan nanah dan darah. Perutnya masih membusung dan sewaktu-waktu mungkin akan meledak juga. Di layar itu pula kami bisa melihat sepasang bibir Ayah senantiasa tersenyum aneh, matanya memandang fokus kamera yang sepertinya telah ia ketahui. Ia seperti tengah mengejek kami yang durhaka dengan senyum itu dan dengan cara memandangnya yang tak wajar.
Para dokter terus berusaha untuk menyembuhkan penyakit Ayah. Namun, apalah daya para dokter. Mereka hanya tahu asal muasal nafas dan tak tahu dari mana, serta kapan datang dan perginya nyawa.
Kecemasan kami memuncak ketika tiba-tiba, di layar kaca itu, nampak perut Ayah meledak, persis seperti gunung berapi yang meletus. Ayah meninggal dengan tubuh dipenuhi nanah kental yang bercampur dengan darah yang keluar dari perutnya yang meledak. Susah bagi kami untuk mengatakan berduka cita atas kematiannya. Tapi susah pula untuk mengatakan kami berbahagia.
***
Tak bisa kami bayangkan saat semua harta yang kami miliki amblas jika kami mengubur mayat Ayah. Puluhan rumah megah, ratusan kendaraan mewah, hotel, restoran, dan villa yang tersebar di seluruh kota, triliyunan uang di berbagai bank, berkilo-kilo emas, batu permata dan berlian yang kami miliki akan hilang begitu saja ditelan bumi. Dan jika semua yang kami miliki itu akan benar-benar amblas ke bumi, kami mengira akan terjadi gempa berkekuatan besar melanda negeri ini. Gempa itu tentu tidak hanya akan menewaskan kami, tapi juga ribuan orang lainnya.
Kami kemudian berkumpul untuk memilih siapa di antara kami yang akan dicalonkan dalam pemilihan nanti. Kami berempat telah siap menggantikan Ayah menjadi pemimpin kota ini.
Tapi, tiba-tiba saja bau busuk menyergap hidung kami. Sekejap melintas pertanyaan dalam pikiran kami, adakah mayat Ayah telah membusuk. Meski kami tidak melihatnya dalam layar kaca itu, karena tubuh Ayah tertutup rapat oleh kain hitam, tapi kami mulai mencium bau busuk itu dari pakaian yang kami kenakan. Bola mata kami semakin tajam memandang layar kaca yang merekam tubuh Ayah. Tapi kian lama gambar dalam layar kaca itu kian pudar. Mungkinkah layar itu juga ikut membusuk. Pandangan kami kemudian beredar ke sekeliling ruangan. Kami melihat warna tembok yang tadinya putih bersih berubah menjadi kecokelatan. Kami berdiri, berjalan mendekat, merabanya, dan dapat kami rasakan tembok itu basah dan bau busuk keluar darinya. (Sofa, meja, lukisan, dan semua benda yang kami kenakan juga mengeluarkan bau busuk).
Di sela-sela kebingungan itu, kakakku yang paling tua mengusulkan untuk membakar mayat Ayah. Kontan aku dan kedua kakakku tidak setuju. Kami tidak ingin semua harta kami akan hangus terbakar. Dan apa jadinya dunia ini jika semua harta kami terbakar.
Dalam keadaan seperti itu aku berlari ke meja telpon untuk menghubungi perawat yang masih berjaga di kamar tempat Ayah tergolek tanpa nyawa. Aku menyuruhnya untuk mengawetkan mayat Ayah. Pilihan ini lahir dari kebingunganku.
Dengan wajah menggurat cemas, kami memandang layar monitor yang buram. Di sana, samar-samar kami lihat mayat Ayah tengah disemprot zat pengawet oleh perawat yang mengenakan masker. Tubuhku mendadak kaku! **
Yogyakarta, 2006-Wonosobo, 2013