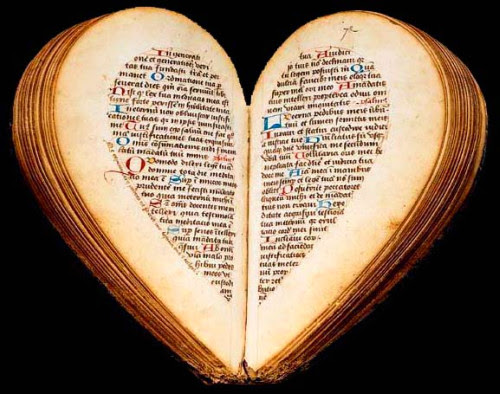Sore dengan
langit jingga selalu menjadi waktu kesukaanku. Saat langit berpendar dengan
arakan awan berwarna merah keemasan dan pilar-pilar cahaya yang menembus
kumpulan awan yang lebih tebal menghujam ke bawah lalu hilang membias sebelum
menyentuh bumi, semuanya begitu menakjubkan. Dikejauhan, di sela-sela
pegunungan yang menggelap sisi depannya, mentari sore bergerak perlahan begitu
pelan menghilang keperaduannya, menyisakan cahaya jingga kemerahan yang
mengintip malu-malu. Mungkin aku terlalu berlebihan, tapi memandang lukisan
alam yang begitu menakjubkan ketika melintasi jalan di tengah areal persawahan
ini begitu menenangkan, hatikupun terasa ringan melayang. Sejenak aku lupa
dengan segala kegelisahan yang akhir-akhir ini begitu akrab dengan diriku.
Aku berdiri
di bibir pembatas jalan, melayangkan pandanganku ke hamparan sawah yang ada di
bawahku. Padi yang baru mulai tumbuh tampak menggelap, menampilkan ilusi danau
beriak tertiup angin. Sore yang jingga, sore yang indah mulai menghilang,
digantikan oleh pekatnya malam berangin semilir yang meniup kegelisahan
kehatiku lagi. Aku pun beranjak pulang. Rumahku tak jauh dari tempatku sering
menghabiskan sore, ‘jalan baru’ kami menyebutnya, walaupun jalan di tengah
areal persawahan ini tak lagi baru, 5 tahun mungkin tak kurang usianya semenjak
jalan ini diaspal dan menjadi akses alternatif menuju kota. Langkahku pulang
diiringi suara adzan maghrib dari surau tua di dekat rumahku. Aku harus bergegas
atau aku akan ketinggalan sholat maghrib berjamaah lagi. Aku tidak mau kuping
bapakku panas mendengar bisik-bisik tetangga yang menggunjing tentang anak
lelakinya yang tidak rajin ke surau, pulang main-main tidak penting dan lupa
sholat. Tinggal di desa kecil di daerah pedalaman yang kultur budaya
religiusnya begitu kental haruslah selalu sholat berjamaah di surau atau
masjid, kalau tidak bersiaplah menjadi bahan gunjingan tetangga.
Aku berusia
16 tahun, tapi aku masih kelas 3 SMP padahal teman-temanku sudah kelas 1 SMA.
Aku pernah tidak naik kelas waktu SD jadi aku tertinggal satu tingkat dari
teman-temanku. Aku tidak pernah menyesali ketidaknaikkanku itu. Ibuku selalu
bilang, aku tidak boleh terlalu menyesali sesuatu. Penyesalan selalu datang
diakhir, jadi kata ibu, sebelum penyesalan itu datang aku harus berusaha keras
dan berdoa kepada Allah agar segala sesuatunya dilancarkan. Akan tetapi jika
kenyataan tidak seperti yang aku harapakan, itu bukan karena aku gagal tapi
karena Allah punya rencana lain untukku. Jadi jangan pernah menyesal apa lagi
menyerah. Itulah ibuku, perempuan sederhana yang berprinsip dan penyayang. Aku
juga tak akan menyesal karena tertahan satu tahun di SD waktu itu. Aku tidak
naik bukan karena aku bodoh tapi karena aku dulu sakit tifus sampai 2 bulan
lalu guru kelas 3 ku tidak menaikkanku dengan alasan terlalu banyak pelajaran
yang aku lewatkan.
Bapakku
seorang petani. Beliau pendiam dan pemikir. Tak banyak yang bapak ucapkan jika
memang tidak perlu tapi menurutku bapak kadang bicara banyak juga. Bapak bicara
banyak atau bercerita hanya kepada orang yang beliau kenal baik, orang yang
akan setia mendengarkannya tanpa banyak menimpali hal-hal yang tidak disukainya.
Siapa lagi kalau bukan dengan ibuku. Aku tahu karena ibu sering
memperingatkanku untuk tidak boros, untuk rajin sholat, belajar dan bergaul
yang benar dan itu semua kata beliau adalah atas suruhan bapak. Bapak juga
tidak marah-marah atau mengata-ngataiku dengan hal-hal yang buruk, tapi jika
beliau sudah terlanjur emosi dan tak tahan maka beliau akan langsung bertindak.
Aku masih ingat, waktu itu bapak melepaskan sandalnya dan melemparkannya kepada
ku gara-gara beliau menyangka aku mengganggu adikku sampai menangis. Padahal adikku
menangis gara-gara temanku yang menjahilinya. Aku lari ke tegalan di belakang
rumah dan sampai takut mau pulang. Sejak
saat itu aku berjanji untuk tidak membuatnya marah. Meskipun saat itu ketika
aku mengendap-endap pulang beliau telah menungguku di samping kamar mandi,
tempat yang pasti akan aku tuju karena hari telah sore dan aku harus mandi.
Bapak menungguku dan memandikanku. Aku tahu bapak menyesal telah melempariku
dengan sandalnya walaupun tidak kudengar beliau meminta maaf padaku tapi aku
tau dari sorot matanya ketika menungguku dan membelai kepalaku yang
dikeramasinya dengan lembut. Aku masih ingat saja kejadian itu walau sudah lama
berselang, ketika aku duduk dikelas 2 SD.
Bukankah
tadi aku bilang kalau akhir-akhir ini aku gelisah? Aku ingin menceritakannya
padamu. Aku juga akan memberitahu kalian kenapa aku suka menghabiskan waktu
soreku di jalan baru tengah sawah itu.
***
Maya adalah
teman sekelasku. Dia tinggal di lain desa dan aku hanya berjumpa denganya di
sekolah. Maya duduk di depanku dengan Dika, bendahara kelas. Maya anaknya
pemalu. Sering kali ketika guru kami memberinya pertanyaan dia menjawab tanpa
berani menatap langsung sang guru. Begitu pula ketika teman-teman menggodanya,
dia hanya tersipu, menahan senyumnya dan memerahlah pipinya. Berbeda dengan
Dika yang lebih pemberani. Mungkin dia adalah siswa perempuan yang paling
berani di kelasku. Dia tak segan memprotes guru yang sering terlambat bahkan
menantang panco guru olah ragaku. Mereka begitu kontras.
Setiap hari
aku melihat maya dari belakang. Aku senang melihat rambutnya yang bergelombang
sebahu. Aku suka memandangi punggungnya, entahlah aku suka saja. Rambutnya
harum dan pakaiannya segar, menghirupnya dari belakang ketika ada angin yang bertiup
membuatku bersemangat belajar. Tapi aku paling suka ketika melihat dia
tersenyum dan pipinya merona. Dia manis.
Tapi
seminggu ini aku belum melihat dia tersenyum. Dia tampak lebih pendiam walaupun
biasanyapun dia tidak banyak bicara. Tapi aku tahu dia murung. Aku bukan teman
dekat Maya tapi karena aku selalu duduk di belakangnya maka aku tahu ada yang
tidak biasa dengannya. Saat bel istirahat berbunyi anak-anak berhambur keluar.
Membeli makanan ringan atau minuman di kantin adalah hiburan. Aku tidak punya
banyak uang jajan. Kadang jika ibu punya uang lebih aku diberinya uang saku
tapi jika tidak aku juga tidak meminta. Aku cukup sarapan saja di rumah. Biar
Ijal, adikku yang mendapat uang saku. Hari ini ibu memberiku 500 rupiah. Aku
sudah akan berjalan melewati pintu ketika aku menyadari hanya Maya yang tidak
keluar kelas. Dia tampak malas memasukkan bukunya ke dalam tas, tatapannya
kosong. Aku mengurungkan niatku. Aku berjalan kearah bangkunya dan bertanya,
“Ada apa Ya? Kok sepertinya dari tadi diam saja. Sakit ya?” “Eeh.. Wan, aku
tidak apa-apa. Malas saja rasanya.” “Kok tumben malas. Apa tidak ingat kata pak
Agus, kelas tiga gak boleh malas ujian sudah dekat,” kataku tidak percaya
mendengar jawaban Maya. “Itu dia. Andaikan saja ujian masih jauh... Kamu kalau
mau beli makanan beli saja. Aku gak apa-apa kok.” “Iya. Kalau beneran tidak
apa-apa ya sudah. Kalau perlu bantuan bilang saja jangan sungkan ya” Aku sebenarnya
heran mendengar Maya berkata seperti itu. Tidak biasanya siswa sepintar seperti
Maya mengeluh tentang ujian. Aku saja sudah tidak sabar untuk bisa sekolah di
SMA, artinya aku bisa lebih sering pergi ke kota Kabupaten. Tapi entahlah, aku
pergi keluar kelas ke perpustakaan sekolah.
Betapa rapuh
hati ini saat melihat orang yang kita cintai sakit. Begitu pula dengan temanku
yang manis, Maya. Ibunya sakit-sakitan sejak melahirkan adiknya dua tahun yang
lalu. Aku tahu ibu Maya sakit karena aku melihat Maya, ibunya, ayahnya dan
seorang lelaki naik sebuah mobil sedan berwarna biru telur bebek melintas di
jalan baru ketika aku sedang duduk di pinggir sawah petang itu. Kira-kira dua
minggu yang lalu. Mobil itu melintas cukup pelan karena memang aspal di jalan
itu sudah tidak rata lagi. Aku melihat ibunya bersandar lemas di bahu suaminya
dan Maya memijit lengan ibunya. Ketika aku tahu ada Maya di dalam mobil itu,
aku berdiri agar bisa melihat siapa saja di sana. Aku sempat melihat maya
memandangku tetapi ketika mobil itu semakin mendekati tempatku berdiri, Maya
membuang mukanya dariku. Aku tidak tahu kenapa. Keesokan harinya, di sekolah
aku bertanya kepadanya tentang apa yang kulihat kemarin sore. Benarkah itu dia.
Maya menjawab benar. Mereka mengantar ibu ke Puskesmas untuk dirawat di sana. Kondisinya
tiba-tiba drop setelah pulang dari ziarah Wali Songo. Aku juga bertanya siapa
lelaki yang mengemudikan mobil itu tapi Maya tidak mau menjawab. Dia pergi
dengan alasan ada keperluan dengan temannya di kelas lain.
Aku tidak
pernah berpikir macam-macam tentang hal yang tidak jelas tapi kejadian sore itu
mau tak mau membuatku penasaran juga. Itu adalah sore keempat setelah aku
melihat Maya mengantarkan ibunya ke Puskesmas. Apalagi akhir-akhir ini ada yang
berubah dari sikapnya. Sore itu, ketika aku sedang duduk di pinggir sawah
seperti hari-hari biasa. Menatap langit sore yang jingga, mengingat kata-kata Bapak
ketika aku masih kecil bahwa langit sore yang seperti ini namanya Candikolo. Aku juga tidak tahu apa
maksud dari istilah itu tapi Bapak bilang pada saat langit sore jingga keemasan
dan awan bercahaya, itu menandakan bahwa gerbang kerajaan langit sedang dibuka
untuk mengizinkan para bidadari masuk kembali ke istana. Aku begitu tertarik
dengan sepenggal cerita yang Bapakku biasa katakan ketika mengajakku
duduk-duduk di teras depan rumah. Aku selalu ingin tahu di mana letak istana
itu dan seperti apa bidadari itu tapi Bapak bilang itu mustahil karena jika
kita berlama-lama melihat Candikolo sampai Adzan Maghrib berkumandang kita bisa
diculik raksasa. Oleh karena itu sebelum gelap tiba kita harus segera pergi ke
surau.
Ya, sore itu
senja jingga, Candikolo sedang terpampang di langit Tuhan. Aku tidak mau
melewatkannya maka aku pergi ke jalan baru untuk menikmati pemandangan itu. Selang
lima belas menit aku duduk di pembatas jalan, aku melihat mobil sedan warna
telur bebek itu lewat. Mobil itu berjalan perlahan kearah utara. Aku ingat itu
adalah mobil yang membawa ibu Maya ke Puskesmas. Pandanganku kualihkan ke mobil
itu. Aku melihat lelaki dewasa berusia sekitar 30 tahunan mengemudi dan
seseorang lagi sedang duduk di kursi sebelahnya. Dia tidak memandang ke depan
ataupun ke arahku. Seseorang itu sepertinya tidak ingin aku tahu siapa dirinya
tapi aku tahu siapa dia. Dia adalah gadis berambut sebahu. Maya, siapa lagi.
Semakin hari
aku semakin merasa suka dengan Maya. Mungkin aku sedang jatuh cinta tapi aku
tidak mengatakannya. Bukan aku tidak berani tapi aku merasa ini adalah perasaan
yang aneh tapi sekaligus menyenangkan. Aku tidak tahu harus berbuat apa setelah
aku mengatakan kalau aku menyukainya. Yang aku tahu, jika seorang lelaki
menyukai seorang perempuan maka tidak lama kemudian mereka akan menikah. Seperti
Mas Ahmadi tetanggaku dan mbak Karmila dari desa sebelah. Aku tidak mungkin
menikah setelah lulus SMP, aku ingin sekali bersekolah lagi. Tapi hari ini aku
tidak bisa tinggal diam. Di kelas, wali kelasku memanggil Maya ke depan. Beliau
bertanya dengan suara pelan ke Maya tapi aku bisa membaca dari bibirnya apa
yang Ibu wali kelas tanyakan. Beliau menanyakan tentang uang LKS sebesar Rp. 105.000
yang rupanya belum dibayar oleh Maya padahal semua teman sekelas telah
melunasinya. Maya tampak hanya tertunduk diam. Aku tidak tahu apa yang dia katakan
karena dia berdiri membelakangiku.
Pada jam istirahat,
ketika teman-teman yang lain pergi ke kantin aku berhenti di samping bangku
Maya. “Kamu belum bayar uang LKS ya?” tanyaku. Dia tampak terkejut lalu
berkata, “Iya belum, belum ada uang.” Aku agak heran dan tidak percaya
mendengar jawaban itu. “Kamu kan tahu kalau akhir minggu ini adalah batas
pembayarannya dan ini juga sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian
akhir. Bagaimana nanti?” tanyaku kepada Maya. “Aku tahu Wan, besok aku bisa
bayar kok. Hari ini hanya lupa tidak bawa saja.” “Apakah benar seperti itu?
Jika kamu butuh bantuan mungkin aku bisa meminjamimu sedikit. Aku ada tabungan
atau pinjam ibuku.” “Tidak, tidak Wan. Jangan, terima kasih. Kamu tidak perlu melakukan
itu, aku sebenarnya ada uang kok.” Keherananku bertambah, “Lalu kenapa tidak
segera kau bayar? Aku tidak percaya jika kamu lupa atau tidak punya uang atau
ayahmu belum memberimu. Jika benar orang tuamu belum punya uang, paman atau
saudaramu yang punya mobil itu pasti bisa meminjamimu kan?” aku tidak menyangka
jika kalimat yang aku ucapkan tanpa pikir panjang ini akan membuat suasana berubah
drastis. Aku melihat perubahan ekspresi di wajah Maya, dia tampak lebih tegang
dan sedih. “Wan, itu bukan pamanku atau saudaraku,” kata Maya dengan suara
bergetar. “Aku lebih suka tidak lulus dari pada harus meminta uang kepadanya.”
Matanya sekarang berkaca-kaca dan aku jadi bingung. “Ada apa Ya? Lalu dia
siapamu?” “Sudahlah Wan, aku tidak ingin membicarakannya.” “Tapi aku peduli
denganmu May, aku tidak ingin kamu mendapat masalah sehingga kamu tidak lulus. Aku
ingin bisa bersekolah lagi sama-sama kamu.” Maya memandangku dengan ekspresi
terkejut tapi dia tidak berkata apa-apa. Beberapa teman masuk ke kelas membawa
makanan dan minuman mereka, aku menghentikan percakapanku dengan Maya.
Sore itu
tidak ada Candikolo, langit sore gelap karena mendung tebal. Aku tidak pergi ke
jalan baru karena memang hujan tampaknya akan turun. Aku sedang membantu Ijal
mengerjakan PR nya ketika ibu datang dan berkata, “Wan, anak perempuan Bu
Aminah yang tinggal di desa sebelah itu teman satu sekolahmu ya?” “Anak Bu
Aminah? Siapa ya Bu?” “Itu yang rumahnya dekat Balai Desa. Dia agak sering
sakit-sakitan setelah melahirkan.” Aku ingat sekarang, “Oh, mungkin itu ibunya
Maya. Iya anaknya teman sekelas Wawan. Ada apa Bu kok tiba-tiba bertanya
tentang dia?” “Maya ya namanya,” ibuku bertanya tapi lebih ke dirinya sendiri,
aku tidak perlu memberinya jawaban. “Anaknya cantik ya Wan?” Aku tertawa
mendengar ibu yang tiba-tiba bertanya seperti itu. “Hmm ya cantik bu, manis. Memang
kenapa bu? tanyaku lagi. “Ibu dengar dari ibu-ibu di Jamaah Yasinan, si Maya
itu mau dinikahkan selepas lulus dari SMP ini.” Kata-kata ibu sangat
mengejutkanku. Aku terbelalak tidak percaya mendengar apa yang ibu katakan. “Yang
benar bu?” “Ibu juga kurang tahu, Wan. Kata ibu-ibu dia akan dilamar sama Deni
anaknya Pak Abu pemilik toko bangunan di desa situ.” Percakapan kami terputus
sampai disini karena kudengar suara Bapak memanggil Ibu dari dapur. Aku tiba-tiba
merasa lemas. Perasaanku tidak enak sekali. Aku tidak tahu kenapa tapi hal ini
kurasakan setelah aku mendengar bahwa Maya mau dinikahkan. Ada perasaan tidak
rela yang sulit untuk aku jelaskan.
Hari ini
Maya tidak masuk sekolah, di papan absensi tertulis izin. Aku jadi menduga-duga
kalau acara lamaran itu berlangsung hari ini. Rasanya sungguh tidak adil bagi
Maya dan akupun turut geram membayangkannya. Tapi siapa tahu, Maya juga
menghendakinya. Sore ini aku membawa sepedaku ke jalan baru, ke tengah areal
persawahan tempat aku biasanya menghabiskan sore. Aku mengayuh sepedaku
cepat-cepat. Pukul setengah lima tapi hari sudah mulai gelap. Mungkin senja
berwarna jingga akan muncul. Dari kejauhan aku melihat seseorang duduk di
pembatas jalan yang bisanya aku gunakan untuk duduk. Aku penasaran siapa yang
telah merebut tempat favoritku itu. Semakin dekat semakin jelas siapa yang
terlihat disana. Gadis berambut sebahu dan sepeda jengki berwarna gelap. Jantungku
berdegup kencang, mungkin karena aku terengah-engah mengayuh sepedaku terlalu
kencang atau mungkin saja karena hal lain. “May, kenapa kamu ada disini?” Dia
tersenyum sebentar lalu kembali memandang gunung di barat sana, ke semburat
jingga keemasan yang mulai merebak. “Aku tahu sekarang kenapa kamu suka ada di
sini hampir setiap sore Wan. Aku melihatmu beberapa kali ketika melewati tempat
ini tapi kamu tidak mempedulikan jalanan yang ada di belakangmu. Sore di sini
begitu indah.” “Iya aku suka melihat langit di sini. Candikolo itu selalu membuatku
tertarik sejak aku masih kecil. Tapi kenapa kamu tumben kesini? Tadi pagi kamu
juga tidak masuk sekolah.” Maya menjawab pertanyaanku tanpa memandangku, “Iya,
aku juga ingin menikmati hari-hari terakhirku di SMP. Aku tahu tempat ini bagus
jadi aku kesini.” Aku jarang sekali mendengar Maya berbicara sebanyak ini, dia
biasanya pendiam. “Aku tidak masuk sekolah hari ini karena dilamar sopir sedan
biru itu.” Kata-kata Maya begitu tajam. Suaranya terdengar menahan luapan emosi.
Aku hanya diam. “Aku akan segera menikah Wan. Kamu tidak akan melihatku di SMA
manapun. Menikah.” Suara Maya tidak setajam tadi, aku mendengar getaran di
suara itu. Getaran kegetiran dan ketidakrelaan. “Kenapa Ya? Kamu tidak suka
bersekolah? Itu juga alasanmu tidak segera membayar kan?” “Aku sangat ingin
bersekolah Wan, tapi orang tuaku memintaku untuk berhenti sampai SMP saja. Tak baik
menolak pinangan orang, itu kata mereka” kata Maya menahan tangis. “Kamu tidak
bisa menolaknya?” tanyaku. “Aku sudah pernah menolaknya tapi Ibuku berkata ini
adalah pemintaannya yang terakhir, Wan. Ibuku sakit-sakitan, beliau ingin
melihatku berumah tangga sebelum Allah memanggilnya. Aku tidak bisa berbuat
apa-apa mendengar Ibu berkata seperti itu. Bapakku pun setuju saja. Aku tidak
punya pilihan lain.” Kami berdua berdiri terdiam. Memandang langit yang
sekarang bercahaya keemasan dan awan yang merah kekuningan. Lalu aku memecah
kesunyian itu, “Aku harus mengucapkan selamat atau apa ke kamu Ya? Jika saja
aku sudah dewasa, aku ingin membantumu. Tapi sekarang ini akupun tak tahu harus
berkata apa atau berbuat apa untuk membantumu. Itupun jika kamu benar-benar
membutuhkan bantuan.” “Kamu tidak perlu melakukan apa-apa, Wan. Aku bahagia
sekali bisa berada di sini melihat pemandangan ini bersamamu. Ini cukup
membantuku.”
Lalu suara
sedan kecil warna biru telur bebek itu terdengar berhenti. Aku menoleh dan
melihat lelaki itu keluar dari mobilnya. Dia memanggil Maya, setengah berteriak
marah karena melihat calon istrinya bersama lelaki lain di pinggir sawah pada
jam seperti ini. Maya berbalik, dia berjalan menuju ke sepedanya. Dinaikinya sepeda
itu lalu dia beranjak. Aku masih mendengar dia berkata ‘terima kasih, Wan’
sesaat sebelum mobil itu mengiringinya. Aku kembali melihat ke langit di barat
sana. Cahaya jingga mulai meredup menghilang dan bidadari telah pulang ke
istananya. Aku mendengar sayup suara Adzan Maghrib dari surau dekat rumahku. Akupun
harus pulang.
By Supra D’Ocean